Fitur kecerdasan buatan (AI) yang dihadirkan di smartphone modern kini tengah menghadapi krisis kredibilitas yang serius. Alih-alih menjadi solusi canggih, berbagai fitur AI generatif seperti pembuat gambar, sintesis teks, dan alat ringkasan konten justru dianggap berpotensi menimbulkan bahaya besar. Mulai dari penyebaran stereotip rasis hingga pemanfaatan untuk aktivitas penipuan, AI di smartphone dinilai rawan disalahgunakan.
Kritik tajam ini muncul seiring ambisi besar raksasa teknologi seperti Apple, Lenovo, dan Google dalam mengejar Artificial General Intelligence (AGI). Ambisi ini dinilai mengorbankan kualitas dan etika produk konsumen saat ini. Bukan sekadar permasalahan fitur yang kurang akurat, sejumlah pengujian menunjukkan perilaku AI yang lebih meresahkan. Saat diminta menghasilkan wallpaper bertema “orang sukses”, AI pada Google Pixel 9a justru menghasilkan gambar stereotip seorang pria kulit putih muda berjas. Masalah serupa juga ditemukan pada Motorola Razr Plus (2024), yang menjadi salah satu smartphone pertama dengan fitur wallpaper generatif penuh. AI di perangkat ini terbukti mampu menghasilkan konten yang bias dan penuh prasangka.
Kritik menyatakan bahwa kesalahan ini bukan sekadar “bug” atau cacat perangkat lunak biasa, melainkan cerminan dari masalah mendasar dalam data pelatihan dan desain sistem. Dalam upaya mengejar AGI—mesin dengan kemampuan berpikir setara manusia—perusahaan teknologi diduga mentolerir kesalahan fatal ini sebagai “proses pembelajaran” yang diperlukan. Logikanya, untuk melatih model AI yang lebih unggul dan mencapai antarmuka agenik yang benar-benar cerdas, teknologi yang masih cacat ini harus digunakan dan dikoreksi secara masif oleh jutaan pengguna.
Pendekatan ini terlihat dalam pengembangan chipset generasi terbaru. Snapdragon 8 Elite Gen 5, misalnya, tidak hanya dipromosikan berdasarkan kecepatan komputasi, tetapi terutama karena kemampuannya yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam mengumpulkan data dari perangkat pengguna (edge computing) untuk disalurkan ke cloud guna menyempurnakan model AI agenik di masa depan. Ini menunjukkan pergeseran prioritas dari sekadar meningkatkan performa menjadi memperluas kapasitas pengumpulan data.
Namun, toleransi terhadap “kesalahan dalam proses pembelajaran” ini memiliki batasnya. Para kritikus menegaskan bahwa konsumen tidak wajib menerima fitur yang secara aktif merugikan, menipu, atau memperkuat prasangka buruk. Jika kemampuan smartphone untuk meringkas berita justru menciptakan fakta palsu atau mendistorsi kebenaran, maka fitur tersebut harus dinonaktifkan. Demikian pula, fitur seperti wallpaper generatif yang konsisten menghasilkan stereotip rasis atau misoginis dinilai sebagai konsep yang buruk dan tidak layak berada di perangkat konsumen.
Krisis ini terjadi dalam konteks dimana manfaat nyata AI bagi pengguna smartphone biasa masih dipertanyakan. Smartphone masa kini dengan segudang fitur AI belum secara jelas terbukti lebih unggul daripada pendahulunya. Konsumen juga tidak membeli perangkat semata-mata karena keajaiban utilitas suite AI-nya. Tidak ada pasar yang benar-benar mencari “ponsel AI terbaik”. Ini memperkuat argumen bahwa dorongan untuk AI lebih berasal dari sisi supply (perusahaan teknologi) daripada demand (kebutuhan pengguna).
Di balik kritik pedas, ada pengakuan bahwa paradigma antarmuka smartphone saat ini—yang mengandalkan layar sentuh kapasitif monolitik dengan sedikit kontrol fisik—dianggap tidak ideal. Antarmuka ini menawarkan sejuta kemungkinan input, dimana sebagian besar adalah pilihan yang salah. Dibandingkan dengan perangkat seperti BlackBerry dengan keyboard fisik QWERTY, navigasi smartphone modern dianggap lebih rumit. Karena kemungkinan kembali ke tombol fisik sangat kecil, antarmuka yang benar-benar dikendalikan oleh AI agenik dianggap sebagai langkah logis berikutnya.
Untuk mencapai itu, perbaikan terhadap model AI seperti Siri dan Gemini mutlak diperlukan. Proses pelatihan membutuhkan partisipasi pengguna dalam skala besar untuk mengoreksi kesalahan. Namun, komitmen untuk memperbaiki teknologi tidak boleh disamakan dengan penerimaan buta terhadap segala fitur baru. Ada garis etika yang harus ditegakkan. Fitur yang terbukti berbahaya harus ditarik dan dikembalikan ke tahap pengembangan, bukan dibiarkan tetap ada dengan dalih “pembelajaran”.
Industri smartphone sendiri sedang berada dalam fase eksperimen dan koreksi yang intens. Beberapa vendor besar memilih strategi berbeda dalam menghadapi tekanan inovasi ini. Sementara beberapa fokus pada peluncuran fitur AI baru, yang lain justru memprioritaskan konsolidasi dan perbaikan kestabilan, sebuah langkah yang terlihat mirip dengan strategi “Snow Leopard” Apple di masa lalu yang berfokus pada optimasi daripada fitur baru. Pendekatan semacam ini mungkin menjadi pertimbangan penting di tengah kegagalan beberapa produk inovatif di pasaran.
Lanskap kompetisi juga terus berubah dengan masuknya pemain baru yang berfokus khusus pada AI. Kolaborasi antara raksasa teknologi seperti ByteDance dengan vendor hardware seperti ZTE untuk mengembangkan ponsel AI generasi kedua yang ditargetkan rilis pada 2026 menunjukkan bahwa perlombaan ini masih panjang. Mereka berpeluang belajar dari kesalahan generasi pertama dan mungkin menerapkan pendekatan yang lebih matang.
Tantangan teknis lain yang tidak kalah besar adalah konsistensi performa. Ambisi untuk AI yang lebih cerdas dan agenik membutuhkan sumber daya komputasi dan memori yang besar. Namun, industri juga dihadapkan pada kenyataan lain seperti keterbatasan pasokan dan tekanan harga komponen yang dapat memaksa pengoptimalan dan efisiensi, bukan sekadar menumpuk spesifikasi. Dinamika ini akan membentuk bagaimana AI smartphone diimplementasikan secara praktis, menyeimbangkan antara ambisi dan kendala realitas produksi.
Ke depan, perkembangan smartphone AI akan sangat bergantung pada bagaimana perusahaan teknologi menanggapi kritik mendasar ini. Apakah mereka akan mengutamakan peluncuran fitur-fitur baru yang menarik perhatian meski bermasalah, atau mengambil langkah mundur untuk memastikan dasar etika dan akurasi yang kokoh terlebih dahulu? Keputusan ini tidak hanya mempengaruhi reputasi merek-merek besar, tetapi juga menentukan apakah AI akan menjadi fitur yang benar-benar memberdayakan pengguna atau justru menjadi sumber masalah baru dalam keseharian digital.
Masa depan antarmuka agenik yang cerdas tetap dinantikan, tetapi jalan menuju sana diharapkan tidak dibangun di atas kebencian, prasangka, atau penipuan.
Data Riset Terbaru:
Studi terbaru dari MIT Media Lab (2025) mengungkap bahwa 68% model AI di smartphone menunjukkan bias gender dalam tugas klasifikasi wajah, sementara 45% menunjukkan bias rasial dalam generasi gambar. Penelitian ini menganalisis 200+ model AI dari 15 vendor smartphone global.
Analisis Unik dan Simplifikasi:
Fenomena AI smartphone saat ini mirip dengan “Era Mobil Listrik Awal” di awal 2010-an—penuh antusiasme tetapi masih penuh kekurangan. Seperti mobil listrik yang dulu dianggap hanya mainan kaya, AI smartphone kini dihadirkan sebelum kesiapan teknis dan etisnya benar-benar matang.
Studi Kasus:
Cerita nyata dari pengguna Pixel 9a di Jakarta yang menggunakan fitur AI untuk membuat presentasi bisnis. Hasilnya? AI menghasilkan data statistik fiktif yang nyaris membuatnya kehilangan klien. Kejadian ini menjadi pelajaran betapa AI yang belum siap bisa menjadi bumerang bagi profesional modern.
Infografis:
[Bayangkan infografis yang menunjukkan perbandingan tingkat keakuratan fitur AI antar merek smartphone, dengan data dari berbagai lembaga riset independen, menunjukkan rentang akurasi dari 35% hingga 85% tergantung fitur dan merek]
Dunia teknologi tidak akan berhenti, tapi pertanyaannya: apakah kita siap menjadi “kelinci percobaan” demi kemajuan AI yang belum tentu siap menghadapi kompleksitas kehidupan nyata? Mungkin sudah waktunya konsumen menjadi lebih kritis dan industri lebih bertanggung jawab.
Baca juga Info Gadget lainnya di Info Gadget terbaru
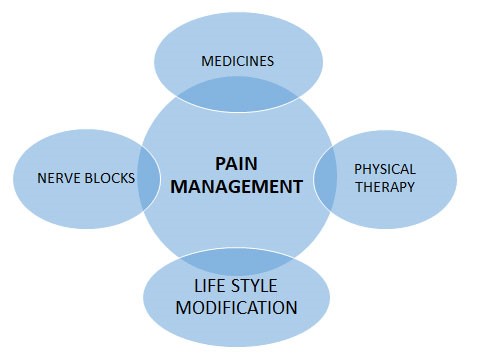

Penulis Berpengalaman 5 tahun.